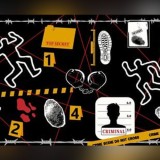TIMES BOJONEGORO, BOJONEGORO – Di ruang kelas yang terang lampunya, guru itu tampak luwes. Rancangan pembelajaran tersusun rapi, tujuan pembelajaran jelas, media terpadu, penilaian berbasis kompetensi. Di era penilaian kinerja, papan portofolio digital guru penuh dengan screenshot kegiatan inovatif, siswa tampak antusias, nilai ulangan meroket.
Pada lembar observasi, indikator “kemampuan pedagogik” centang semua. Di mata kurikulum, sekolah itu beres. Di lapangan, yang terjadi sering berbeda: anak-anak lulus dengan kognisi yang menanjak, tapi karakter yang buyar.
Ini bukan lontaran umum tanpa bukti. Dari kunjungan ke beberapa sekolah menengah di kota-kota kecil hingga sekolompok pondok pesantren modern, peta masalahnya berulang: guru semakin mahir menyusun strategi pembelajaran tetapi minim waktu dan ruang untuk membangun moral dan karakter yang konsisten.
Fakta lapangan sederhana: jam pembelajaran penuh dengan materi, diskusi, dan proyek. Namun kegiatan pembentukan karakter sering diserahkan pada acara seremonial seminggu sekali: upacara, pidato motivasi satu kali, atau sesi “sharing” yang sifatnya formalitas. Sementara itu, kasus-kasus bullying, plagiarisme tugas, dan kepekaan sosial yang rendah tetap tampak sehari-hari.
Kenapa bisa begitu? Sebagian jawabannya ada pada tekanan sistem. Guru dinilai lewat indikator ketercapaian akademik dan dokumentasi inovasi pembelajaran. Insentif, apresiasi, bahkan peluang karier sering terkait dengan angka-angka itu.
Maka wajar jika energi diarahkan untuk “mengoptimalkan” pedagogi mencari metode paling efektif agar siswa lulus uji kompetensi, mengangkat reputasi sekolah lewat prestasi akademik, dan memenuhi KPIs yang dipatok dinas. Namun ketika semua instrumen diarahkan ke sana, pembentukan moral dan karakter yang subtansial menjadi korban tak terlihat.
Fakta lapangan lain yang sering saya lihat: program pembinaan karakter jika ada sering bersifat episodik dan diseragankan. Satu bulan ada tema anti-bullying, bulan berikutnya sosialisasi kebersihan, lalu pembinaan kepemimpinan. Intinya baik, tetapi tanpa kesinambungan.
Karakter butuh pengulangan, model, dan konteks; bukan seminar sekali lalu selesai. Ketika lingkungan sekolah tidak menginternalisasi nilai-nilai itu setiap hari dalam aturan kelas, diskusi, penanganan konflik, serta hubungan antara guru-siswa maka pembelajaran moral menjadi sekadar latar yang mudah dilupakan.
Ada juga masalah kompetensi moral pada pendidik sendiri. Tidak semua guru dilatih untuk menjadi fasilitator karakter. Mereka ahli materi, mahir menyampaikan isi pelajaran, tetapi minim pelatihan praktis soal mentoring emosional, resolusi konflik, dan pendidikan etik.
Di beberapa sekolah, guru yang jadi “mentor moral” hanyalah yang punya selera religius atau aktivitas ekstrakurikuler bukan bagian dari job description formal. Akibatnya, pembelajaran karakter bersandar pada inisiatif individu, bukan sistem yang merata.
Dampaknya nyata. Di satu SMA negeri di Kota X, saya menyaksikan situasi di mana siswa paham teori demokrasi dapat menjelaskan pasal-pasal, sejarah, dan praktik pemilu tetapi di lapangan ketika berdiskusi, kecenderungan untuk memotong pembicaraan, menghina lawan argumen, atau merendahkan teman yang berbeda pendapat menjadi hal biasa.
Di satu madrasah, santri cakap dalam hafalan ilmu agama, namun ketika ada masalah sosial di lingkungan, respons mereka cenderung pasif karena belum dilatih ketrampilan empati dan kepemimpinan sosial.
Kritik ini bukan menolak pentingnya pedagogi yang baik, justru sebaliknya. Pedagogi yang mumpuni harusnya menjadi jembatan menuju pembentukan manusia utuh: yang berpikir kritis, punya kompetensi, dan sekaligus beretika.
Kita butuh guru yang tidak hanya paham teknik mengajar, tetapi juga mampu menanamkan karakter lewat rutinitas pembelajaran misalnya: memberikan ruang refleksi harian singkat, memodelkan etika dialog, mengaitkan materi akademik dengan tanggung jawab sosial, serta menegakkan konsekuensi yang mendidik ketika pelanggaran terjadi.
Solusinya mesti sistemik. Pertama, kurikulum dan standar penilaian harus mengukur bukan sekadar kompetensi akademik, tetapi indikator karakter yang konkret: empati, tanggung jawab, integritas, dan keberanian moral. Bukti lapangan perlu menjadi bagian dari asesmen, bagaimana siswa menyelesaikan konflik, berkolaborasi, atau menunjukkan kepedulian sosial.
Kedua, pelatihan guru harus memasukkan modul mentoring karakter yang praktis latihan simulasi, coaching, dan supervisi rutin.
Ketiga, sekolah mesti jadi laboratorium nilai: aturan, kebijakan disiplin, hingga kegiatan ekstrakurikuler harus sinkron membentuk karakter setiap hari, bukan sekadar acara.
Kita harus realistis: perubahan tidak terjadi semalam. Tetapi membiarkan jurang antara pedagogi dan moral terus melebar artinya kita sedang mencetak generasi setengah jadi cerdas secara teknis, miskin secara etis.
Dalam masyarakat yang kompleks ini, kompetensi tanpa kompas moral mudah disalahgunakan; pengetahuan tanpa rasa tanggung jawab bisa jadi sumber kekacauan.
Tugas ini bukan hanya guru atau kepala sekolah; ini tanggung jawab kolektif: dinas pendidikan, perguruan tinggi yang melatih guru, orang tua, dan komunitas. Kalau kita ingin generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga bermartabat, maka investasi terbesar bukan sekadar di ruang kelas ber-AC atau modul digital melainkan pada pembentukan hati dan karakter yang dijalankan setiap hari, dalam setiap interaksi kecil yang, lama-kelamaan, membentuk siapa mereka sebenarnya. (*)
***
*) Oleh : Ida Fauziyah, Mahasiswa PPG Calon Guru, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |